Pada usia 14 dan 16 tahun, Ayan dan Farhan hanyalah remaja biasa di kampung halaman mereka di Quetta, Pakistan. Pergi ke sekolah, bermain bola sepak, dan membantu ibu mereka berbuat ini dan itu.
Pada satu hari, ibu mereka menghantar mereka pergi ke bandar bersebelahan untuk membeli ubat-ubatan yang tidak ada dijual di tempat mereka. Bukan kali pertama mereka ke sana, sudah banyak kali sebelum ini.
Tetapi, perjalanan kali itu akan mengubah hidup mereka.
Tidak terlintas di fikiran mereka, itulah kali terakhir mereka dapat melihat wajah ibu mereka, melihat kampung halaman tempat mereka membesar. Tidak pernah mereka terfikir itulah permulaan kepada perjalanan panjang mereka ke Malaysia, sendirian.
Inilah kisah mereka seperti yang diceritakan kepada Aidila Razak.
Sebelum kami lahir, ada perang saudara di Afghanistan, tempat asal-usul keluarga kami. Ayah kami petani, pada masa itu ada dua lagi adik-beradik di atas kami.
Ayah dan pakcik saya tuan tanah. Sebelum perang saudara, ada perselisihan tanah, iaitu ada tanah yang dirampas secara paksa. Ayah dan pakcik saya menentang perampasan itu. Oleh itu mereka jadi agak berpengaruh di kawasan itu.
Pengaruhnya semakin besar dan besar, dan bila perang saudara itu berlaku, ayah saya menjadi sasaran. Oleh kerana itu, keluarga saya - ibu bapa dan dua adik beradik sulung - melarikan diri ke bandar Hazaran di Quetta, Pakistan.
Di Hazara, ibu dan bapa saya mendapat lagi empat orang anak. Kami (Farhan dan Ayan) anak yang tengah, nombor empat dan lima. Kami tak pernah ada dokumen.
Quetta ialah bandar yang sangat besar, tapi kami banyak tinggal dalam lingkungan Hazara sahaja. Ia bahagian kecil daripada Quetta. Kami jarang keluar ke bandar.
Jalan di Hazara sempit-sempit, tak banyak kenderaan, dan budak-budak akan main di jalan, main guli, main layang-layang. Sebelum ayah kami meninggal dunia, kadang-kadang kami akan tolong dia di kedai pakaian dia. Tapi pada kebanyakan hari, kami pergi sekolah dan bermain dengan kawan-kawan di jalan, main bola sepak.
Hari itu, mak kami hantar kami ke satu bandar berdekatan untuk beli ubat. Kami dah banyak kali ke sana. Tapi kali ini, ada sekatan jalan.
Mereka ambil telefon kami, bawa kami ke balai polis, dan tahan kami di situ selama dua hari. Kami tak dibenarkan menghubungi keluarga.
Pada hari kedua, kami diarah naik trak. Masa itu sudah malam. Mereka tak beritahu apa-apa pun. Ramai orang di dalam trak itu. Akhirnya, kami sedar, kami dibawa menuju ke sempadan Afghanistan.
Dalam perjalanan itu, kami terfikir tentang keluarga kami, tentang mak kami. Kami bimbangkan dia - apalah dia fikir nanti bila kami berdua pergi tak pulang-pulang.
Trak itu turunkan kami di sempadan sebelah Afghan. Inilah kali pertama kami jejak kaki ke tanah Afghan. Ada juga orang-orang lain yang diusir pada masa itu, tapi mereka tak ambil kisah pasal kami. Kami tak tahu nak buat apa, kami takut.
Ada kedai-kedai di sempadan itu, dan kami pun ada duit daripada ibu kami yang dia bagi untuk kami beli ubat. Jadi benda pertama yang kami buat, kami beli telefon dan kad sim untuk telefon rumah.
Dalam panggilan telefon itu, satu perkara yang kami ingat ibu pesan: “Buatlah apa-apa sekali pun, asalkan (dapat) balik ke rumah”.
Ibu kata, ada orang boleh tolong, yang boleh bawa kami balik ke Pakistan kalau kami bayar upah.
Di sempadan, ada satu hotel. Ibu pesan untuk ke situ dan minta tolong sesiapa yang boleh bawa kami menyeberang sempadan. Kami tak tahu siapa yang boleh kami percaya, tapi kami tak ada pilihan.
Kami cuba seberang sempadan tiga kali dalam tempoh tiga hari kami di bandar di sempadan itu.
Kali pertama kami cuba nak seberang sempadan, seberang macam biasa sahaja. Agen itu sepatutnya berunding dengan pengawal sempadan dan kami sepatutnya dapat menyeberang. Tapi tak berjaya. Kawalan sempadan agak tegas. Perkara sama terjadi pada cubaan kali kedua.
Hari sudah malam, dan keadaan sangat gelap. Kami mula bergerak, hanya berpandukan cahaya bulan. Kami ikut seorang lelaki yang membawa kami masuk ke hutan, melalui kawasan gunung. Kami tak tahu arah tuju kami, kami hanya ikut sahaja. Ia berterusan untuk beberapa jam.
Begitupun, kami tak berjaya menyeberang. Kawalan sempadan sangat ketat. Kami tak dapat sampai ke seberang dengan selamat. Jadi kami patah balik.
Ibu beritahu kami, bahaya untuk kami terus tinggal di Afghanistan kerana mereka yang menentang arwah ayah akan cari kami jika mereka tahu kami ada di negara itu. Ibu pesan: “Cari jalan untuk keluar dari Afghanistan”.
Abang sulung saya, yang telah berpindah ke Australia, ada usulkan cadangan - kalau tak dapat menyeberang ikut jalan darat, kami boleh cuba ikut jalan udara. Untuk lakukan ini, kami perlu ke Kabul dan mohon pasport. Dengan pasport itu, kami boleh dapatkan visa dan naik penerbangan ke Pakistan.

Kabul jauhnya lebih 500km dari sempadan. Mengenangkan pesanan ibu, perjalanan itu menjadi sangat menakutkan. Tapi kami tak ada pilihan.
Kami menunggu seminggu untuk mendapatkan pasport, dan dalam masa itu, abang kami ada masukkan sedikit duit supaya kami dapat bertahan. Setelah lebih seminggu hidup dalam penuh ketidakpastian, keadaan mula menampakkan sinar harapan. Tapi apa yang kami tak tahu, adalah mustahil untuk kami mendapatkan visa atau pun penerbangan ke Pakistan.
Hubungan antara Afghanistan dan Pakistan tegang pada masa itu, dan tak ada penerbangan antara kedua-dua negara. Pada masa itulah, kami ambil keputusan untuk ke negara lain - ke mana-mana sahaja, asalkan keluar dari Afghan.
Kami melawat satu agen pelancongan, dan agen itu beritahu, dengan pasport Afghan kami itu, satu-satunya visa yang kami boleh dapat ialah visa ke Malaysia. Kami tak tahu apa-apa tentang Malaysia. Tapi abang kami cakap, “Okay, dari Malaysia kamu boleh pergi tempat lain”. Jadi kami setuju.
Kami tak bawa apa-apa dengan kami. Kami ada beberapa pasang pakaian yang dibeli di Kabul dan sedikit duit yang abang hantar. Itu sajalah.
Kami betul-betul keliru sepanjang penerbangan kami ke Malaysia. Kami risau apalah yang akan terjadi kepada kami apabila mendarat nanti? Siapa nak bantu kami? Macam mana kami nak berkomunikasi?
Perjalanan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur lancar. Kami ada visa, jadi tak ada isu di imigresen. Tapi sebaik sahaja pintu lapangan terbang dibuka, kami terkejut. Bila kami tinggalkan Afghanistan, cuaca sejuk. Di sini, macam ada orang lempar api kepada kami.
Kami tak tahu nak pergi mana, jadi kami telefon agen pelancongan yang tolong tempah tiket kapal terbang kami. Dia suruh kami dapatkan teksi dan beritahu pemandu teksi untuk bawa kami ke Ampang.
“Orang-orang kamu ada di Ampang,” katanya. Tapi kami tak tahu sesiapa di sana. Jadi rancangan kami, pergi saja dulu ke sana, dan kemudian cari orang yang bercakap bahasa kami.
Kami sampai Ampang masa tengah hari - mungkin dalam pukul tiga petang. Pemandu teksi berhenti berdekatan Ampang Point. Tak ramai orang di jalan raya pada masa itu, dan kami dengar, tak ada sesiapa pun yang bercakap bahasa kami. Jadi kami ambil keputusan untuk duduk di tepi jalan dan tunggu.
Kemudian tak lama kemudian, menakjubkan sekali, ada sekumpulan lelaki berjalan melepasi kami dan kami dengar mereka cakap bahasa Parsi. Mereka pun berhenti bila nampak kami.
“Kamu baru (tiba)kah di Malaysia?” tanya mereka. “Ada tempat untuk tinggal?” Kami beritahu, kami tak ada sesiapa. Mereka bawa kami ke pangsapuri kecil mereka tak jauh dari situ. Mereka beritahu, mereka akan tolong kami.
Melalui merekalah, kami sedar rancangan asal kami untuk ke Australia bagi bertemu dengan abang kami bukanlah sesuatu yang mudah. Melalui mereka juga, kami sedar yang kami kini bergelar pelarian.
Mereka beritahu kami, jalan terbaik adalah untuk mendaftarkan diri dengan UNHCR (agensi PBB untuk pelarian). Mungkin UNHCR boleh bantu kami.
Kami tinggal di pangsapuri itu untuk dua bulan, dan sepanjang masa itu, yang lain-lain di situ membantu kami. Kami tak pernah memasak sebelum ini, jadi pada awalnya kami hanya hidup dengan memakan mi segera Maggi, sehinggalah abang-abang di situ ajar kami memasak makanan yang ringkas-ringkas.

UNHCR banyak membantu. Kami diberikan kad - sesuatu yang kami tak pernah miliki di Pakistan. Sebelum dapat kad itu, kami bimbang sebab kami hanya ada visa, itu pun sudah hendak luput tarikh.
Kami berpindah dari pangsapuri di Ampang apabila kami dihubungkan dengan Suka Society, yang membantu pelarian bawah umur yang terpisah dengan keluarga masing-masing. Suka bantu kami dapatkan tempat tinggal dengan satu keluarga angkat dan carikan kami sekolah.
Sudah dua tahun sejak kami tiba di Malaysia. Bila saya ceritakan kisah kami, saya beritahu, apa yang kami harungi rasanya seperti apabila kamu di dalam air, dan arus membawa kamu ke mana-mana sahaja ia tuju. Kamu tak mampu sangat nak kawal, tapi kamu kena terus hadapi, terus kuat, teruskan juga ke mana-mana saja ia bawa kamu.
Kena sabar, kena jadi kuat. Jika ia bawa kamu ke pulau, maka hiduplah di atas pulau itu. Jika ia bawa kamu ke negara lain, maka hiduplah di negara itu. Biasakan diri. Hidup.
Sebenarnya, kami bertuah. Kami ada abang kami yang beri panduan pada mula-mula dulu, kemudian ada mereka yang kami jumpa di Ampang, dan pelarian-pelarian lain yang bantu kami fahami proses-proses ini, kemudian ada Suka.
Ada orang lain datang ke Malaysia yang terpaksa bermalam di taman-taman kerana mereka tak ada tempat berteduh. Kemudian mereka harus mula bekerja untuk menampung hidup, meskipun pada usia sebegitu (muda).
Bila kami mencecah umur 18 tahun, Suka tak dapat membantu kami lagi. Mungkin ia kemungkinan yang menakutkan, tetapi kami tidaklah fikir ia sebagai sesuatu yang terlalu menggerunkan. Setiap sesuatu ada masanya, dan itulah masanya untuk teruskan kehidupan. Kami perlu cari jalan untuk teruskan ke depan.
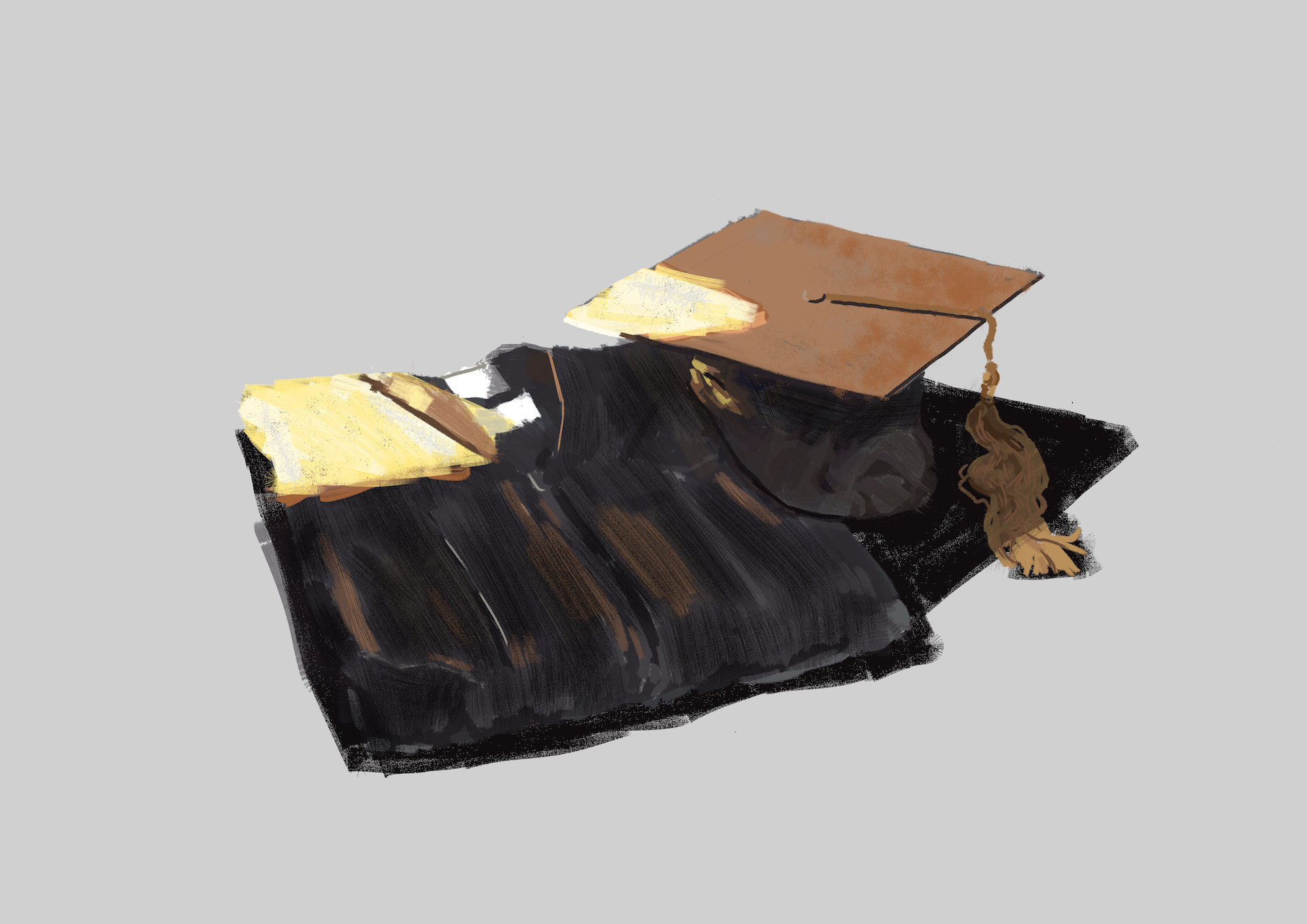
Dalam keadaan yang ideal, kami mahu ke Australia dan hidup dengan abang kami, tapi itu bukanlah dalam kuasa kami. Ia terpulang kepada UNHCR dan kerajaan Australia. Apa yang boleh kami buat ialah tinggal di sini, belajar, dan tunggu.
Sekolah kami ialah sekolah untuk pelarian. Ada empat orang guru yang mengajar sains, matematik, dan pengajian sosial. Ini bukanlah apa yang kami harapkan, tapi dalam masa sukar sebegini, ini sajalah yang kami mampu dapat.
Untuk masa hadapan, kami harap sesuatu yang lebih baik. Sama ada dalam sukan atau dalam pelajaran, kami mahu berjaya dalam hidup. Tai kami juga tak ada kenal mana-mana pelarian yang dapat pergi universiti. Mungkin had pelarian macam kami ini sekadar International General Certificate of Secondary Education (IGCSE).
Sejak saya tinggal di sini, saya dapati ada sebahagian rakyat Malaysia yang memandang pelarian sebagai kelompok manusia yang berbeza daripada diri mereka. Mungkin sesetengah pelarian pun fikir macam itu juga tentang rakyat Malaysia. Tapi mereka semua silap.
Tak ada orang yang berbeza. Kita semua sebenarnya sama sahaja. Satu-satunya hal yang membezakan kita adalah dokumen.




